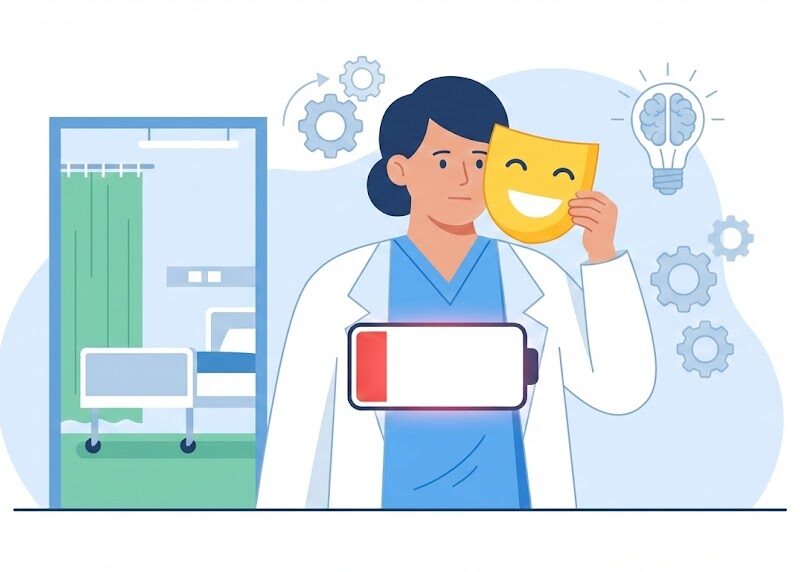Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya (biasanya dilakukan oleh laki-laki). Yang sering terjadi adalah KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis. Meskipun sempat menurun dari 2018 hingga 2021, kasus KDRT kembali meningkat di sepanjang tahun 2022. Data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan, sepanjang 2022 tercatat 18.138 penyintas KDRT di Indonesia.
Terjadinya KDRT bermula dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas. Karena perannya sebagai kepala keluarga, laki-laki merasa memiliki hak untuk membenarkan perlakuannya terhadap istri. Pembenaran penggunaan otoritas ini lahir karena adanya budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia. Dalam budaya patriarki, perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua yang harus tunduk terhadap laki-laki.
Simone de Beavuvoir dalam The Second Sex menyebutkan bahwa dalam masyarakat patriarki, perempuan dipandang sebagai Liyan (sesuatu yang lain) dan tidak sama dengan laki-laki. Jika laki-laki adalah seorang subyek, maka perempuan diartikan sebagai obyek. Dampaknya, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” dan terkait dengan keyakinan serta sikap yang melandasi.
Dalam masyarakat dengan ketimpangan relasi kekuasaan antara pria dan wanita, di mana akses ke sumber daya tidak setara dan peran gender tradisional memperkuat dominasi pria, menyebabkan wanita mungkin takut balas dendam atau tidak dipercaya saat melaporkan adanya KDRT. Norma budaya yang menekankan privasi keluarga juga mencegah wanita mencari bantuan eksternal, mempertahankan keengganan untuk membawa isu-isu keluarga ke publik. Selain itu, sikap menyalahkan penyintas dalam masyarakat, seperti keyakinan bahwa perilaku provokatif wanita menyebabkan kekerasan, menciptakan suasana yang tidak mendukung pelaporan. Wanita mungkin ragu-ragu karena takut akan penilaian atau kesalahan tambahan.
KDRT yang sebelumnya dianggap masalah privat, kini telah dijadikan masalah publik. KDRT diatur dalam Undang-Nndang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT). UU PDKRT telah tegas menyebutkan bahwa KDRT adalah pelanggaran HAM. Sayangnya, implementasi UU ini belum masksimal. Bias gender sering terjadi saat penanganan pelaporan kasus KDRT. Sebab, perempuan masih diposisikan sebagai pihak yang lemah dan memiliki ketergantungan kepada laki-laki, baik secara ekonomi ataupun emosional. Seringkali kondisi ini dijadikan cara jitu untuk membuat penyintas mencabut tuntutan dan berubah menempuh jalan damai. Hasilnya, fungsi UU PDKRT yang harusnya melindungi perempuan menjadi sia-sia.
Sampai saat ini banyak perempuan yang mengalami kekerasan namun enggan melaporkan apa yang dialaminya. Hal ini bisa dijelaskan dengan teori siklus kekerasan. Ketika kita melihat KDRT sebagai siklus yang memengaruhi psikologis penyintas dan kecenderungannya untuk melapor, kita bisa membaginya menjadi tiga tahap yang berbeda.
Tahap pertama dari siklus kekerasan, yang disebut “tension building” (membangun ketegangan). Siklus ini dimulai dengan meningkatnya ketegangan secara bertahap, di mana pelaku menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Pada tahap ini, penyintas cenderung enggan melaporkan kekerasan yang mulai mereka alami karena takut hal itu akan memicu ketegangan yang lebih parah.
Tahap kedua, yang disebut “the incident” (kejadian), ditandai dengan terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Pada tahap ini, perempuan umumnya takut akan balasan dari pasangan yang melakukan kekerasan jika melaporkan kejadian tersebut. Sebab, pelaku sering menggunakan ancaman untuk mencegah penyintas mencari bantuan, termasuk ancaman memutus dukungan finansial dan mengisolasi penyintas dari keluarga dan teman.
Tahap ketiga, yang merupakan periode “honeymoon” (bulan madu), ditandai dengan penyesalan dari pelaku atas tindakan mereka. Mereka mungkin meminta maaf atau berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Ini bisa membuat penyintas merasa simpati pada pelaku dan menumbuhkan harapan baru bahwa kekerasan tidak akan terulang.
Selama fase ini, pelaku juga mungkin mencoba untuk memindahkan tanggung jawab pada penyintas untuk meminimalkan keparahan keadaan yang sebenarnya dibuat oleh pelaku. Pada tahap ini, penyintas dapat meremehkan keparahan kekerasan atau meyakinkan dirinya bahwa KDRT yang dialaminya hanyalah insiden yang terisolasi dan tidak akan terulang, sehingga membuat pelaporan terasa tidak perlu.
Faktor lain yang mungkin ikut andil adalah kurangnya dukungan dari institusi dan sistem hukum yang tidak mendukung bagi perempuan yang ingin melaporkan. Dalam kasus dr Qory, misalnya, setelah mengalami kekerasan fisik, ia baru menyadari dirinya mengalami KDRT. Padahal, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sudah terjadi sejak lama. Bermula dari kekerasan yang dilakukan secara verbal hingga meningkat ke kekerasan secara fisik. Ini karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa KDRT hanya sebagai kekerasan fisik. Padahal, UU PKDRT telah menjabarkan bahwa KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang berakar pada perbedaan berbasis gender.
Dalam sebuah interview dengan media, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara yang menangani kasus KDRT yang menimpa dr. Qory menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dr. Qory dan suaminya masih saling sayang. Sehingga ada rencana pencabutan laporan. “Yang kami tahu memang dan lihat memang pasangan ini saling menyayangi, kemarin kekerasan itu karena dipicu emosi yang memuncak,” ungkapnya.
Ungkapan “saling menyayangi” yang jelas-jelas bukan berasal dari dr Qory ini seolah mengaminkan bahwa pihak berwajib cenderung memihak pelaku dengan cara membuat asumsi bahwa pelaku “tengah berada pada emosi yang memuncak” sehingga “dianggap” wajar untuk melampiaskan emosinya pada penyintas. Di saat yang bersamaan, pelaku “dipercaya” oleh pihak berwajib masih menyayangi penyintas. Dengan asumsi yang diberikan oleh pihak berwajib inilah, penyintas mulai mengurungkan niatnya untuk melakukan pelaporan. Hal ini membuat penanganan kasus KDRT menjadi terhambat, baik karena korban enggan untuk melapor atau karena aparat penegak hukum cenderung berpihak pada pelaku (bias gender).
Hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat penyintas kurang percaya pada kemampuan sistem hukum dan penegak hukum untuk melindungi mereka. Padahal, ketika penyintas dan masyarakat luas percaya bahwa penegak hukum dapat merespons laporan mereka dan melindungi mereka tanpa diskriminasi, tingkat pelaporan KDRT juga akan meningkat. Peningkatan pelaporan kasus KDRT dan penanganan polisi yang lebih efektif terhadap kasus yang dilaporkan seharusnya pada gilirannya mengurangi kejadian dan eskalasi KDRT, dan pada akhirnya mencegah kejahatan yang lebih fatal pada pasangan (misalnya pembunuhan).